
 .
.

Mahkota Emas Kesultanan Siak, Warisan Raja Kecil dari Pagaruyung

Mataxpost | Pekanbaru – Mahkota emas Kesultanan Siak kembali dihadirkan ke publik. Dalam kilau emasnya yang memantulkan cahaya lampu, tak hanya tampak keindahan seni logam Melayu abad ke-18, tetapi juga gema sejarah yang melintasi bukit-bukit Pagaruyung hingga ke tepian Sungai Siak. Bagi yang memahami akar sejarah, mahkota itu bukan sekadar pusaka kerajaan pesisir timur Sumatra ia adalah lambang legitimasi yang berakar dalam darah Minangkabau, warisan seorang anak raja dari ranah Minang yang mengukir takdirnya di panggung besar dunia Melayu. (06/08)
Sejarah mencatat, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, atau yang lebih dikenal sebagai Raja Kecil, lahir di Pagaruyung (Batusangkar-Sumatera Barat) sekitar tahun 1699. Dibentuk oleh tradisi adat dan politik Minang yang menempatkan musyawarah (*kato mufakat*) serta keseimbangan antara adat dan syarak sebagai pilar utama, ia tumbuh di lingkungan istana yang sarat ilmu diplomasi, strategi perang, dan tata pemerintahan. Di bawah bimbingan Puteri Jamilan, ia ditempa menjadi pemimpin dengan visi jauh melampaui tanah kelahirannya.
Memasuki usia dewasa, Raja Kecil merantau ke Palembang, lalu bergerak ke pesisir timur Sumatra sebelum menyeberang ke Johor. Di sana, ia mengklaim sebagai putra Sultan Mahmud Syah II yang terbunuh pada 1699 sebuah klaim yang diperkuat statusnya sebagai bangsawan Pagaruyung. Pada 1718, ia berhasil menaklukkan Johor dan naik takhta sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Namun, konflik internal dengan Bendahara dan tekanan kekuatan Bugis membuat kekuasaannya rapuh, hingga pada 1722 ia terdesak mundur.
Alih-alih kembali ke Pagaruyung, ia memilih membangun kekuasaan baru di tepi Sungai Siak, Buantan. Pada 1722 atau 1723, Kesultanan Siak Sri Indrapura lahir, membawa serta perpaduan adat Minangkabau dan tradisi Melayu pesisir. Gelar kebangsawanan seperti *Datuk*, *Panglima*, dan *Orang Kaya* dipertahankan, prinsip “Baso jo Budi” dijadikan panduan diplomasi, dan sebagian prosesi pelantikan sultan meniru adat Pagaruyung.
Pengaruh Pagaruyung juga tercermin pada mahkota Siak: motif ukiran yang penuh simbol, pemakaian emas murni, serta filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” sebagai dasar pemerintahan. Setiap kali mahkota itu dihadirkan di muka publik, ia menjadi pengakuan terbuka bahwa Siak adalah cabang dari pohon peradaban Minangkabau. “Siak itu rantau, Pagaruyung itu asal, tak bisa dipisahkan., ujar Tuanku Umar seorang budayawan Minangkabau di Pekanbaru.
Meski berdiri sebagai kerajaan merdeka, hubungan Siak dan Pagaruyung tetap erat. Pernikahan antarbangsawan, pertukaran pusaka, hingga kesamaan arsitektur istana membentuk jalur budaya yang tak pernah putus. Sebagian pusaka Siak bahkan diyakini berasal langsung dari Pagaruyung, menjadi bukti konkret bahwa dua kerajaan ini memiliki urat sejarah yang sama.
Kini, ketika mahkota Kesultanan Siak dihadirkan kembali, momen itu tidak sekadar mengenang kejayaan sebuah kerajaan pesisir. Ia adalah panggilan untuk mengingat sejarah asli Siak bahwa di balik kejayaan di tepi Selat Malaka, berdiri seorang putra Minangkabau yang membawa adat Pagaruyung ke rantau, mengubahnya menjadi kekuatan politik, dan menanamkan pengaruhnya di seluruh dunia Melayu.
“Kehadiran mahkota Kesultanan Siak bukan hanya mengenang kejayaan masa lalu, tetapi juga mengajarkan bahwa sejarah Riau berdenyut dari akar yang tertanam di Minangkabau. Memahami Siak berarti memahami Pagaruyung, sebab keduanya adalah satu rangkaian kisah yang tak terpisahkan.”
Kilas cahaya emas di balik kaca bukan hanya pantulan lampu, tetapi gema dari perjalanan panjang seorang raja yang menyeberangi laut, menaklukkan takhta, dan membangun kerajaan baru. Memahami Siak berarti memahami Pagaruyung, sebab keduanya adalah satu kisah, satu darah, dan satu warisan
Sejarah adalah warisan bersama yang kaya, kompleks, dan seringkali dibentuk oleh berbagai sudut pandang. Dalam menelusuri asal-usul identitas dan tokoh-tokoh penting seperti Raja Kecil, penting bagi kita untuk bersandar pada bukti sejarah yang dapat diverifikasi, baik dari naskah klasik, tradisi lisan, hingga catatan kolonial dan penelitian ilmiah.
Namun demikian, penyampaian fakta sejarah tidak dimaksudkan untuk menegasikan identitas kelompok manapun, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman akar budaya yang telah membentuk wilayah Riau dan sekitarnya.
Mari kita jadikan sejarah sebagai jembatan pemahaman, bukan sumber perpecahan. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarahnya secara jujur dan tetap menjaga persatuan dalam keberagaman.
Sumber Referensi:
Hikayat Siak, Tuhfat al-Nafis (oleh Raja Ali Haji), Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Arsip VOC dan catatan perjalanan Thomas Stamford Raffles, “De Maleiers van Siak” oleh P. Voorhoeve, Taufik Abdullah – “Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, M. Junus Djamil – “Sejarah Perkembangan Adat Minangkabau”, Syed Hussein Alatas – “The Myth of the Lazy Native”,
Pengakuan lisan dari:
Suku Sakai, Talang Mamak, Bonai, Petalangan, Anak Dalam, Akit, Anam, dll.













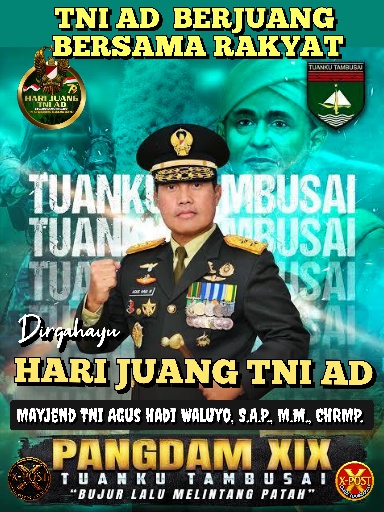








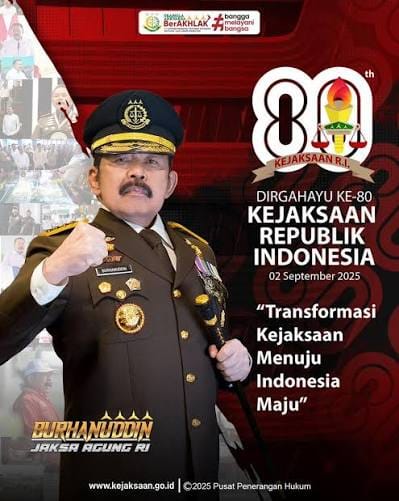 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
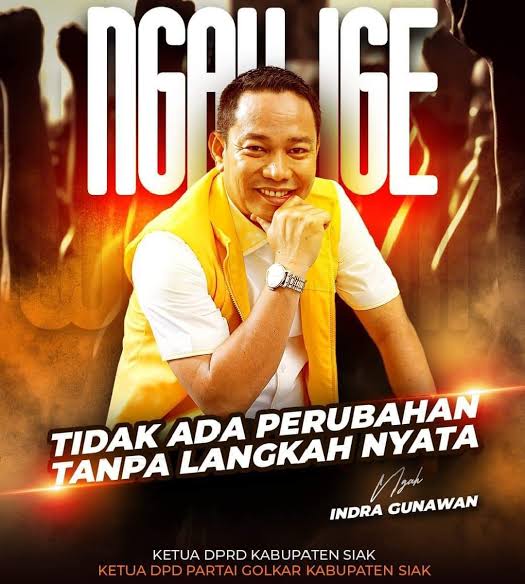 .
.
 .
.
 .
.


Tidak ada komentar