
 .
.

Konspirasi Karbon: Peran Yayasan, Pejabat, dan Mafia Korporasi dalam Perusakan Hutan Riau

Riau, yang dahulu dikenal sebagai jantung hijau Sumatera, kini menjelma menjadi bentang eksploitatif yang memadukan industri kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan tambak udang raksasa di sepanjang garis pantai. Sekitar 3,5 juta hektare hutan alam telah lenyap, digantikan oleh tegakan akasia, eucalyptus, dan kebun sawit milik korporasi raksasa seperti APRIL Group, Sinar Mas Forestry, Wilmar, Asian Agri, dan sejumlah anak usaha PTPN. Riau memang masih tampak hijau, tetapi itu bukan hijaunya hutan lindung, bukan hijaunya mangrove, bukan pula basahnya lahan gambut—melainkan hijaunya kebun sawit terbesar di dunia yang kini dipagari tambak udang dari utara Bengkalis hingga pesisir Indragiri Hilir. (8/7)
Di atas reruntuhan ekologi itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama korporasi dan lembaga lingkungan mengusung narasi pemulihan yang paradoksal melalui skema sertifikasi berkelanjutan RSPO/ISPO dan perdagangan karbon. Skema ini digadang sebagai jawaban terhadap krisis iklim dan deforestasi, tetapi pada praktiknya menjadi instrumen paling mencolok dari greenwashing terstruktur di Indonesia.
Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTTN), yang dibentuk pada 2005 dengan misi konservasi satwa liar dan hutan dataran rendah Sumatera, kini telah berubah fungsi menjadi fasilitator legitimasi hijau bagi korporasi besar. Dalam banyak dokumen sertifikasi RSPO, nama YTTN kerap tercantum sebagai mitra sosial-lingkungan yang memberikan rekomendasi, menyusun dokumen teknis, hingga memediasi konflik masyarakat. Padahal, YTTN bukan lembaga audit independen. Perannya adalah mengemas narasi konservasi dan keberlanjutan agar dapat diterima oleh lembaga audit seperti TUV Rheinland, SGS, atau SCS Global Services, yang kerap menerima laporan tanpa investigasi lapangan mendalam.
Di tingkat pemerintahan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga turut berperan aktif mempercepat legitimasi ini. Alih-alih mengawasi kepatuhan lingkungan dan kehutanan, Disbun justru memfasilitasi percepatan sertifikasi RSPO/ISPO, terutama bagi koperasi petani sawit binaan korporasi. Di Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir, para petani mengakui adanya bantuan luar biasa dari Disbun dalam mempercepat legalisasi dokumen, meskipun sebagian besar lahan mereka berada di dalam kawasan hutan yang belum memiliki pelepasan secara hukum.
PTPN IV dan V, sebagai perusahaan negara, pun mengikuti pola serupa. Mereka menyandang status pelopor sawit berkelanjutan, namun sejumlah konsesi mereka masih berada di kawasan hutan produksi dan lahan gambut yang tidak memiliki kejelasan hukum (unclear and unclean). Mereka menggandeng mitra seperti YTTN dan konsultan lingkungan untuk menyusun laporan inventarisasi flora-fauna, rencana mitigasi sosial, hingga peta kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT). Dokumen-dokumen ini, dalam banyak kasus, tidak pernah diverifikasi dampaknya secara independen.
APRIL Group melalui anak perusahaannya PT RAPP menjadi contoh paling mencolok. Mengelola ratusan ribu hektare HTI di Riau untuk suplai bahan baku pabrik bubur kertas di Pangkalan Kerinci, perusahaan ini tetap mempromosikan citra hijau lewat program restorasi dan proyek perdagangan karbon. Restorasi Ekosistem Riau (RER) di Semenanjung Kampar adalah flagship proyek karbon mereka, diklaim mendapat dukungan finansial lebih dari USD 100 juta selama satu dekade, termasuk dari donor asing, program REDD+, dan mitra offset karbon. Namun, ekspansi HTI di wilayah gambut dan hutan lindung terus berjalan, bahkan menjangkau area yang sebelumnya dipetakan sebagai wilayah konservasi.
Sinar Mas Forestry melalui PT Arara Abadi dan PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) juga mengadopsi pendekatan serupa. Mereka menjalin kemitraan dengan yayasan lokal, universitas, dan lembaga donor untuk membangun citra hijau perusahaan. Kawasan seperti Giam Siak Kecil–Bukit Batu Biosphere Reserve (705.000 hektare), yang awalnya difungsikan sebagai pelindung satwa, kini telah terkepung oleh ekspansi HTI dan menghadirkan konflik agraria masif di wilayah Siak, Bengkalis, dan Dumai. Peran lembaga lokal sering kali hanya formalitas pencantuman nama dalam dokumen AMDAL dan laporan keberlanjutan, tanpa kontribusi nyata di lapangan.
Ironi berlanjut pada praktik aliran dana. Sejumlah yayasan lokal, termasuk YTTN, mendapatkan dana hibah dari lembaga internasional seperti UNDP, NORAD, USAID, GIZ, serta melalui program CSR dari APRIL, Sinar Mas, Wilmar, dan Asian Agri. Dana itu dikemas dalam proyek pelestarian, pemberdayaan masyarakat, dan riset konservasi. Namun, tidak satu pun dari proyek tersebut memiliki laporan audit keuangan publik. Proyek perdagangan karbon berbasis masyarakat hanyalah kedok bagi skema imbal jasa yang menguntungkan elite yayasan, konsultan lingkungan, dan birokrat daerah.
Sementara itu, data lapangan menunjukkan bahwa kerusakan hutan terus berlangsung. Taman Nasional Tesso Nilo yang seharusnya menjadi pusat konservasi gajah Sumatera dan harimau, kini lebih dari 28.600 hektarenya telah rusak. Sekitar 36.353 hektare di antaranya bahkan telah ditanami sawit secara ilegal, sebagian besar terkait dengan rantai suplai Wilmar dan Asian Agri. Kabupaten Rokan Hilir mencatat deforestasi lebih dari 464.000 hektare antara 1990 hingga 2013. Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar, dan Bengkalis menyusul sebagai wilayah dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi. Di seluruh Riau, lebih dari 70% lahan gambut telah dikonversi menjadi perkebunan, dengan sisa sekitar 940.000 hektare kini dalam ancaman serius ekspansi.
Yang lebih mencengangkan, sepanjang pantai Riau kini dibentengi tambak udang yang menggerus mangrove dan meminggirkan nelayan lokal. Proyek tambak ilegal di Rupat Utara, Bantan, Sungai Pakning, Pulau Burung, dan Teluk Belitung telah membuka ribuan hektare lahan pesisir, menggantikan fungsi hutan bakau dan merusak sistem perairan dangkal. Namun, kegiatan ini tidak pernah tersentuh penegakan hukum karena diduga melibatkan kongsi antara pejabat daerah dan pemodal besar dari luar negeri.
Semua skema ini akhirnya bermuara pada satu tujuan: memoles narasi bahwa industri sawit dan pulp and paper di Riau telah berubah menjadi industri hijau dan berkelanjutan. Padahal, realitasnya bertolak belakang. Kebakaran hutan tetap terjadi setiap musim kemarau. Populasi gajah dan harimau Sumatera terus menyusut. Sungai-sungai utama tercemar. Konflik agraria meningkat. Dan komunitas adat seperti Sakai, Talang Mamak, dan Melayu Tua terus kehilangan tanah leluhurnya.
Apa yang terjadi di Riau adalah bentuk paling ekstrem dari greenwashing sistemik. Ini bukan sekadar kegagalan pengawasan, melainkan keberhasilan manipulasi yang melibatkan yayasan lingkungan, birokrasi daerah, BUMN, korporasi global, dan lembaga sertifikasi internasional. Riau hari ini bukanlah contoh keberhasilan restorasi, melainkan panggung besar ilusi hijau yang menyesatkan dunia.










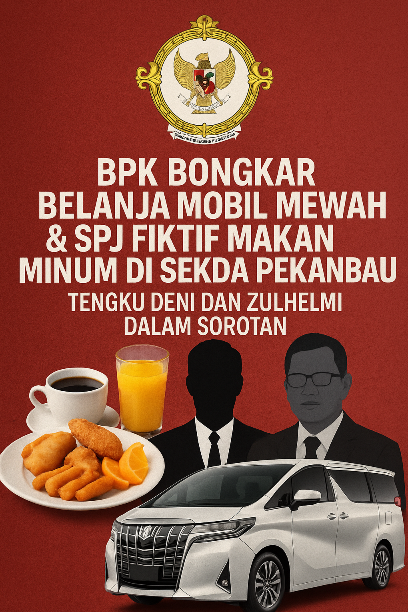
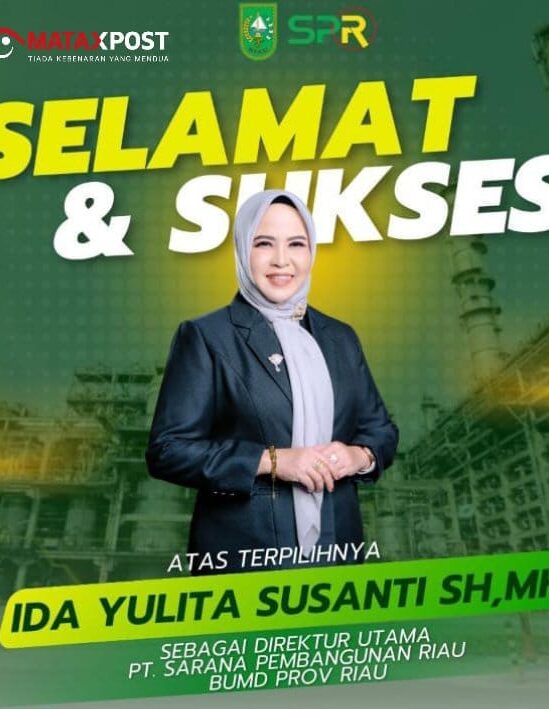


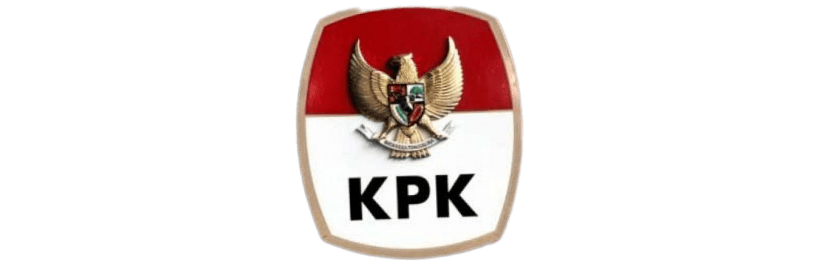












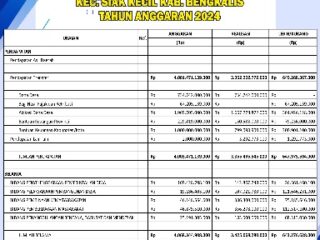
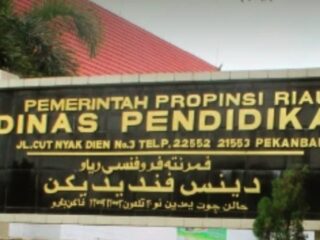


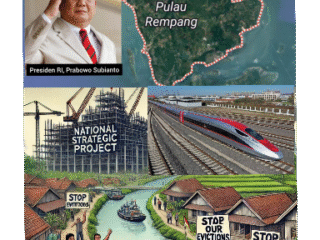




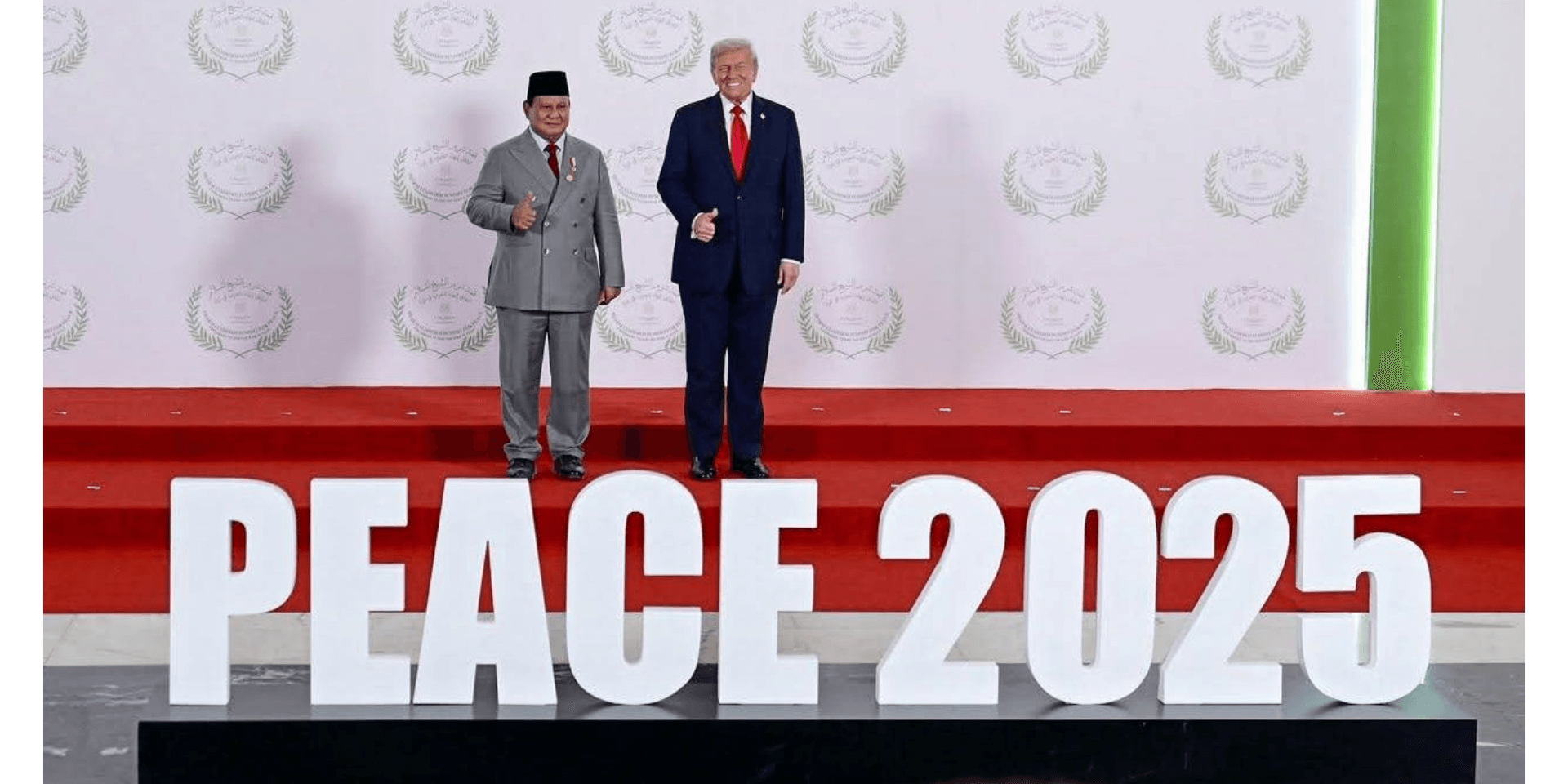
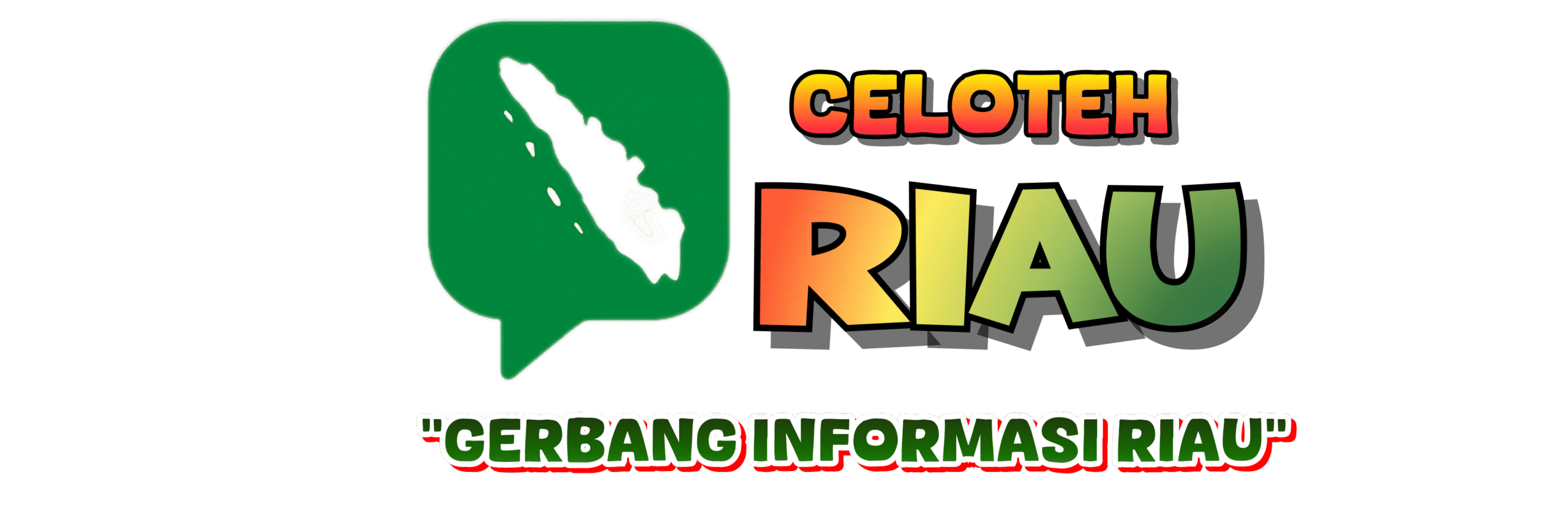


Tidak ada komentar