
 .
.

Gerakan Rakyat atau Rekayasa Kekuasaan? Menguak Operasi Intelijen di Balik Demonstrasi Agustus 2025
 Gambar ilustrasi ( dok: istimewa)
Gambar ilustrasi ( dok: istimewa)Oleh Ruben Cornelius Siagian
Peneliti & Riset Center Cendekiawan, Peneliti Muda Indonesia
Mataxpost | Jakarta, – Demonstrasi nasional yang mengguncang Indonesia pada 25–29 Agustus 2025 menjadi salah satu peristiwa sosial-politik paling mencolok dalam sejarah pascareformasi. Ribuan massa turun ke jalan di lebih dari seratus tujuh puluh kota, memprotes kebijakan tunjangan DPR yang dianggap mencederai rasa keadilan publik. (13/10)
Namun di balik luapan kemarahan itu, muncul pertanyaan yang lebih mengganggu: apakah demonstrasi ini murni letupan rakyat, atau justru bagian dari rekayasa kekuasaan yang sengaja dirancang untuk mengelola bahkan memanipulasi amarah publik?
Secara sosiologis, kemarahan terhadap DPR hanyalah pemantik dari krisis legitimasi politik yang sudah lama menumpuk. Ketimpangan sosial-ekonomi yang kian melebar, gaya hidup elitis para pejabat, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara menciptakan kondisi psikologis yang mudah tersulut.
Teori relative deprivation menjelaskan bahwa ketidakpuasan kolektif muncul ketika masyarakat merasa tertinggal atau diperlakukan tidak adil, terutama ketika kesenjangan antara elite dan rakyat tampak begitu kontras.
Namun yang menimbulkan tanda tanya besar adalah kecepatan mobilisasi publik. Dalam waktu kurang dari dua hari, gelombang protes menyebar ke 173 kota sebuah skala yang nyaris mustahil tanpa jaringan komunikasi yang terorganisasi rapi.
Dalam teori political opportunity structures, gerakan seperti ini terjadi ketika terbuka saluran komunikasi sekaligus melemahnya struktur pengendalian institusi. Dalam perspektif intelijen, kondisi semacam ini disebut window of agitation: momen ketika emosi publik dapat diarahkan secara strategis oleh aktor yang memahami psikologi sosial massa.
Transformasi demonstrasi dari aksi damai menjadi kerusuhan di lebih dari dua puluh persen kota memperkuat dugaan adanya tangan yang mengatur. Munculnya kelompok tak dikenal yang memicu bentrokan, serta kemunculan narasi digital seperti “antek asing” atau “pengkhianat bangsa”, menunjukkan pola controlled chaos kekacauan yang seolah spontan namun sebenarnya terkelola.
Studi tentang operasi intelijen dan konflik intensitas rendah mencatat pola serupa sebagai bagian dari psy-ops atau operasi psikologis, yaitu penggunaan propaganda untuk menggeser makna sosial dan mengendalikan persepsi publik.
Tujuannya bukan sekadar menggerakkan massa, melainkan mengatur siapa yang terlihat heroik, siapa yang dianggap musuh, dan bagaimana masyarakat menafsirkan peristiwa tersebut.
Jika dilihat dari kacamata intelijen politik, operasi seperti ini memiliki beberapa motif strategis. Pertama, untuk mendelegitimasi lembaga publik seperti DPR dan kepolisian agar posisi mereka melemah dalam negosiasi politik.
Kedua, sebagai uji coba sistem keamanan nasional semacam stress test sosial untuk menilai kemampuan aparat menghadapi krisis serentak di berbagai wilayah. Ketiga, sebagai upaya pengalihan isu dari agenda politik yang lebih sensitif, sebagaimana dijelaskan dalam teori agenda-setting media.
Menariknya, respons aparat yang berbeda-beda di setiap kota ada yang represif, ada yang permisif—mengindikasikan adanya lapisan kendali ganda, ciri khas operasi berlapis untuk menguji loyalitas dan disiplin unit keamanan.
Ketika demonstrasi mereda, perang baru dimulai: perang persepsi. Negara menuding adanya provokasi eksternal, sementara kelompok sipil menuduh aparat sebagai dalang kekerasan.
Polarisasi ini mencerminkan praktik perception management manipulasi opini publik yang bertujuan mengalihkan energi sosial dari substansi kebijakan menuju konflik wacana. Di era media sosial, perang persepsi ini semakin tajam.
Algoritma echo chamber memperkuat bias kelompok dan menciptakan ruang gema digital di mana setiap pihak hanya mendengar apa yang ingin mereka percayai. Akibatnya, masyarakat tidak lagi mencari kebenaran, tetapi mengafirmasi keyakinan sendiri.
Dari semua tanda yang terlihat, demonstrasi Agustus 2025 menampakkan dua wajah. Di satu sisi, ia merupakan gerakan rakyat otentik yang berakar pada kekecewaan nyata terhadap ketimpangan sosial dan keserakahan elite. Namun di sisi lain, ia juga menjadi arena bagi rekayasa kekuasaan yang dijalankan secara sistematis.
Amarah sosial yang murni telah dimanfaatkan untuk tujuan politik, menjadikan massa sebagai objek eksperimen dalam strategi pengendalian sosial. Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam praktik kekuasaan modern—dari penguasaan teritorial menuju penguasaan persepsi.
Intelijen masa kini tidak lagi sekadar pengumpul informasi, tetapi telah berevolusi menjadi aktor aktif dalam pembentukan opini publik. Dengan kemampuan memetakan, mengarahkan, dan mengelola emosi sosial, lembaga-lembaga ini memegang kendali terhadap arah dan stabilitas politik.
Namun, tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, fungsi pengelolaan semacam itu mudah bergeser menjadi kontrol sosial yang represif. Demokrasi pun berisiko berubah menjadi teater persepsi, di mana rakyat meyakini diri mereka berdaulat, padahal sesungguhnya sedang diarahkan.
Kita kini hidup dalam ekosistem politik yang sarat distorsi, di mana informasi menjadi senjata dan emosi publik menjadi medan tempur. Di tengah kabut propaganda dan manipulasi digital, batas antara gerakan rakyat dan rekayasa kekuasaan semakin kabur.
Pertanyaan paling mendesak bukan lagi siapa dalang di balik demonstrasi, tetapi apakah demokrasi mampu bertahan dari manipulasi yang dijalankan atas namanya sendiri.
Nb:Tim Riset Center Cendekiawan adalah kelompok peneliti muda yang fokus pada isu demokrasi, kebijakan publik, dan analisis sosial-politik Indonesia.”













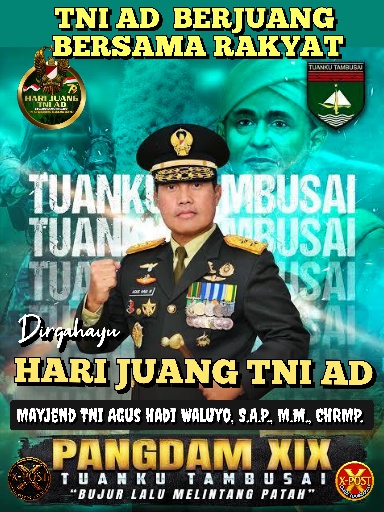








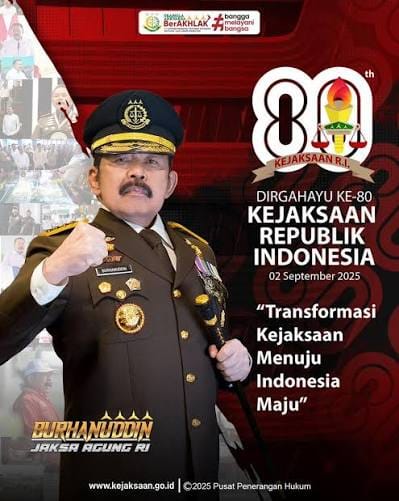 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
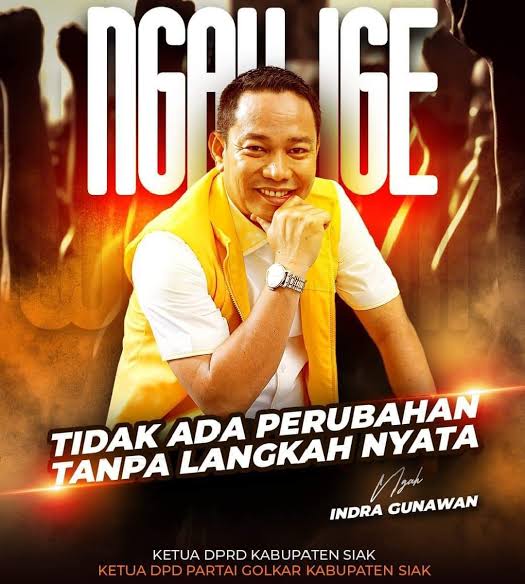 .
.
 .
.
 .
.


Tidak ada komentar