Mataxpost | JAKARTA, – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terus memancing senyum kecut publik. Pasalnya, OTT yang biasanya identik dengan uang di tangan dan pelaku tertunduk, kali ini justru hadir tanpa “tangan basah”. (12/01)
Saat penangkapan dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan uang pada Abdul Wahid.
Penggeledahan di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Riau yang disebut sebagai bagian dari rangkaian OTT juga nihil temuan. Uang yang kemudian diklaim sebagai barang bukti justru ditemukan belakangan, di rumah Abdul Wahid di Jakarta.
OTT tanpa barang bukti di lokasi kejadian ini sontak mengundang pertanyaan. Ibarat razia kendaraan, pelanggarannya ditemukan bukan di jalan, tapi di garasi rumah.
Seiring waktu, cerita perkara pun ikut berubah. Dari OTT, bergeser ke dugaan “jatah preman” (Japrem), lalu bermetamorfosis lagi menjadi perkara gratifikasi.
Pergeseran ini sah secara hukum, namun tetap membuat publik mengernyitkan dahi: yang berubah pasalnya, atau ceritanya?
Dalam hukum pidana, setiap jenis perkara punya syarat masing-masing. OTT menuntut kedekatan waktu dan peristiwa. Pemerasan butuh unsur tekanan.
Gratifikasi mensyaratkan hubungan jabatan dan imbal balik. Ketika uang ditemukan jauh dari lokasi dan waktu penangkapan, pekerjaan pembuktian otomatis naik level dari sprint jadi maraton.
Sampai saat ini, perkara Abdul Wahid juga belum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Masih berputar di ruang penyidikan, membuat publik hanya bisa menebak-nebak sambil menyeruput kopi.
Di tengah ketidakpastian itu, muncul surat tulisan tangan yang diduga berasal dari rumah tahanan KPK. Isinya bantahan dan sumpah pribadi Abdul Wahid. Secara hukum, surat itu tak mengubah apa pun. Namun secara politik, dampaknya terasa.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, terlihat paling keras merespons. Ia menyebut surat itu sebagai “drama politik” dan menuding ada upaya membangun opini publik.
Reaksi ini justru memunculkan pertanyaan baru: mengapa surat yang tak berdampak hukum bisa membuat pejabat yang tidak sedang diadili terlihat paling terganggu?
Alih-alih dibiarkan berlalu sebagai riak opini, surat tersebut justru memantik gelombang pernyataan. Publik pun mulai berspekulasi, apakah kegaduhan ini soal hukum, atau soal kenyamanan.
Satu hal yang pasti, kasus ini menunjukkan bahwa dalam politik dan hukum di Riau Bukan hanya fakta yang berbicara, tapi juga respons para aktornya.
Kadang, yang paling gelisah bukanlah mereka yang duduk di kursi terdakwa, melainkan mereka yang berdiri di sekitarnya.
Ini sebabnya kritik terkuat terhadap kasus ini bukan soal simpati pada Wahid, tapi soal inkonsistensi framing hukum KPK. Hukum pidana tidak alergi pada perubahan pasal, tapi alergi pada perubahan cerita tanpa fondasi bukti yang stabil.
Di pengadilan, jaksa tidak diadili atas niat baik, tapi atas konsistensi logika hukum. Hakim tidak bertanya “ini masuk akal atau tidak”, tapi “ini terbukti atau tidak”.
Jadi kesimpulan dinginnya: bukan mustahil Wahid bersalah, tapi cara perkara ini dibangun membuatnya rawan dipatahkan.
Dan ironi pahitnya begini:
kasus bisa gugur bukan karena terdakwa bersih, melainkan karena penegak hukum tergelincir dalam lompat pagar narasi.
Hukum memang kejam. Ia menghukum yang bersalah. Tapi ia juga tidak segan menghukum aparat yang ceroboh dan kadang, mempermalukan mereka yang terlalu reaktif sebelum waktunya..


 .
.
 .
.
 .
.















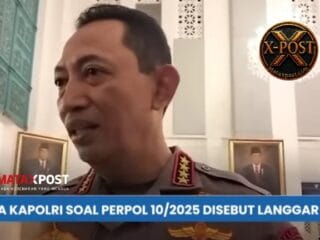












 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.


Tidak ada komentar