
 .
.
 .
.
 .
.

Pertemuan Tokoh Kontroversial di antara Defisit Rp2,2 T, Hibah 1,4 T dan Politik Pengalihan Isu di Riau

Mataxpost | Pekanbaru,- Pertemuan sejumlah elite dan tokoh masyarakat yang menyatakan dukungan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, sejak awal bukan sekadar agenda silaturahmi biasa. Dukungan politik memang lumrah. Yang menimbulkan tanda tanya justru arah pembahasan yang dipilih serta isu-isu besar yang secara sadar tidak disentuh. (06/01)
Forum tersebut dibingkai dengan narasi persatuan, stabilitas, dan kebersamaan. Bahasa yang terdengar menenangkan, tetapi steril dari problem nyata. Dari sekian banyak persoalan serius yang dihadapi Provinsi Riau, Hibah Aset daerah 1,4 Triliun kepada UNRI oleh seorang Plt gubernur dibiarkan senyap tanpa dikritisi.
Fokus diskusi justru mengerucut pada satu isu: pencarian kesalahan Direksi SPR dan pemutusan kontrak kerja sama Hotel Aryaduta. Angka Rp200 juta per tahun disebut berulang kali, seolah itulah penentu utama masa depan fiskal Riau.
Dalam konteks keuangan daerah, angka tersebut nyaris tak berarti. Dibandingkan kondisi APBD Riau yang mengalami defisit hingga Rp2,2 triliun, isu Aryaduta lebih menyerupai etalase politik keputusan simbolik yang aman dibicarakan, cukup keras untuk dipuji, tetapi terlalu kecil untuk membongkar persoalan struktural. Publik diarahkan menatap satu titik sempit, sementara masalah besar dibiarkan di luar sorotan.
Masalahnya, isu Aryaduta sendiri tidak berdiri di ruang hampa.
Tim Redaksi Mataxpost, berdasarkan penelusuran dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta data pengawasan BPKP, justru membongkar fakta yang berlawanan dengan narasi yang kini dipentaskan. Skandal kerja sama Hotel Aryaduta berawal dari kebijakan pada masa Syamsuar menjabat sebagai Gubernur Riau.
Artinya, isu yang kini diangkat sebagai simbol ketegasan dan pembenahan bukanlah warisan tanpa asal-usul, melainkan produk langsung dari keputusan pemerintahan sebelumnya.
Dengan kata lain, publik sedang disuguhi ironi ganda: kebijakan lama dipentaskan ulang sebagai panggung koreksi, tanpa pernah menyebut siapa yang merancangnya sejak awal. Narasi seolah dipotong tepat di tengah akibat ditampilkan, sebab disembunyikan.
Sementara publik diarahkan ke polemik Aryaduta, persoalan yang jauh lebih besar justru luput dibicarakan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, APBD Riau Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sekitar Rp2,2 triliun akibat utang belanja daerah.
Belanja telah direalisasikan tanpa dukungan kas yang memadai. Lebih mengkhawatirkan, penyusunan APBD 2025 belum menunjukkan koreksi struktural yang tegas dan masih menyisakan bayang-bayang masalah serupa.
Defisit ini bukan sekadar persoalan teknis akuntansi. Ia mencerminkan tata kelola keuangan yang longgar, perencanaan yang tidak disiplin, dan pengawasan yang lemah. Defisit tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Syamsuar sebagai Gubernur Riau.
Namun hingga kini, tidak pernah ada penjelasan politik yang utuh kepada publik, apalagi pertanggungjawaban moral. Yang tersisa hanyalah angka merah dan warisan proyek-proyek bermasalah.
Anehnya, dalam forum dukungan elite tersebut, defisit APBD tidak dijadikan isu utama. Tidak ada evaluasi terbuka, tidak ada diskusi kritis, tidak ada penjelasan komprehensif. Yang muncul justru kosakata aman: stabilitas, kebersamaan, dukungan. Bahasa yang nyaman bagi elite, tetapi hampa bagi publik.
Keheningan ini semakin mencolok ketika diingat kasus Hibah Aset Pemerintah Provinsi Riau senilai sekitar Rp1,4 triliun. Ini bukan isu pinggiran, melainkan salah satu persoalan tata kelola aset daerah paling serius dalam sejarah Riau.
Namun dalam pertemuan tersebut, kasus hibah aset sama sekali tidak dibicarakan seolah tidak pernah ada.
Pertanyaan pun mengerucut: mengapa defisit APBD 2024, potensi masalah APBD 2025, dan hibah aset Rp1,4 triliun disenyapkan, sementara isu Aryaduta yang bahkan berakar dari kebijakan lama justru diangkat tinggi-tinggi?
Jawabannya mulai terlihat ketika publik mencermati siapa saja yang hadir. Di antara tokoh pemberi dukungan terdapat Saleh Djasit, mantan Gubernur Riau periode 1998–2003 yang pernah ditangkap dan dihukum oleh KPK.
Hadir pula Arwin AS, mantan Bupati Siak dan mantan terpidana kasus korupsi kehutanan. Ini bukan opini atau insinuasi, melainkan fakta hukum yang tercatat.
Dengan komposisi seperti ini, pilihan isu menjadi masuk akal. Membahas Aryaduta relatif aman. Membuka defisit APBD, membedah APBD 2025, atau mengungkit hibah aset Rp1,4 triliun berarti membuka arsip lama. Dan arsip adalah sesuatu yang tidak semua orang siap hadapi dan apakah ada unsur disengaja menciptakan isu lain untuk tutupi persoalan Hibah ke UNRI tersebut?
Di titik inilah politik simbol bekerja: restu para sesepuh, foto bersama, pernyataan “bersatu”, dan satu isu teknis yang bisa dikendalikan. Ini pola klasik pengalihan isu perhatian publik diarahkan ke satu objek kecil, sementara persoalan struktural dibiarkan tetap gelap.
Ironi bertambah ketika diingat bahwa Riau masih memikul beban proyek-proyek bermasalah. Payung Elektrik Masjid An-Nur menjadi simbol paling telanjang. Digagas sebagai ikon religius-modern,
Ia berakhir sebagai monumen kegagalan perencanaan: tidak berfungsi, konsep runtuh, anggaran habis. Publik pun memberi julukan yang lebih jujur daripada laporan resmi mana pun “jamur kembang tak jadi”.
Proyek Quran Center dan Riau Hub (RCH) menyusul dalam daftar. Dua proyek ambisius yang tampak megah di atas kertas, tetapi kehilangan makna di lapangan. Bangunan berdiri, manfaatnya kabur, pertanggungjawabannya samar.
Di sektor pelayanan publik, dugaan korupsi di RSUD Arifin Achmad menambah lapisan ironi. Rumah sakit rujukan provinsi yang seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat justru terseret persoalan tata kelola. Bahkan ruang yang seharusnya paling steril dari kepentingan ikut tercemar.
Namun dari seluruh persoalan tersebut, narasi dukungan elite tetap memilih Aryaduta sebagai panggung utama. Angka Rp200 juta per tahun disajikan dengan presisi, sementara implikasi hukum, konsekuensi kontraktual, dan fakta bahwa kebijakan itu berasal dari pemerintahan sebelumnya sebagaimana dibongkar Mataxpost lewat dokumen BPK dan BPKP .
Secara jurnalistik, ini bukan iklan, tetapi juga bukan liputan kritis. Ia berada di wilayah soft political endorsement membangun persepsi bahwa stabilitas telah terjaga, sehingga publik diminta tenang dan berhenti bertanya.
Dengan latar defisit Rp2,2 triliun, potensi masalah APBD 2025, hibah aset Rp1,4 triliun, deretan proyek bermasalah, serta fakta bahwa isu Aryaduta sendiri berakar dari kebijakan lama, pertanyaan akhirnya menjadi tajam dan tak terhindarkan:
Stabilitas untuk siapa, dan siapa sebenarnya yang sedang dilindungi?
Kalau disebut janggal, itu masih terlalu halus. Yang terjadi lebih menyerupai pengulangan pola lama. Dalam politik daerah dengan sejarah panjang penindakan hukum, kemunculan kembali tokoh-tokoh lama sering kali bukan tanda pemulihan, melainkan sinyal bahwa siklus lama sedang mencari wajah baru.
Apakah Riau akan kembali “dibersihkan” pada 2026 oleh KPK yang telah 4 kali menangkap Gubernur Riau atau justru Kejaksaan yang akan berikan teguran ke 5 untuk Riau dan ciptakan 1 Gol pertama yang indah? ini bukan soal ramalan.
Penegakan hukum bekerja lewat akumulasi: aliran uang, penyimpangan administrasi, dan bukti yang matang. Jika ketiganya bertemu, pertanyaannya bukan lagi apakah melainkan kapan?
Sejarah Riau sudah memberi pelajaran yang cukup jelas tentang luka.
Arsip tidak pernah lupa, meski aktornya berharap publik lupa. Riau tidak kekurangan pengalaman. Riau justru kekurangan keberanian untuk membuka masalah besar secara jujur. Tenang boleh. Diam terlalu lama, biasanya bukan tanpa alasan.













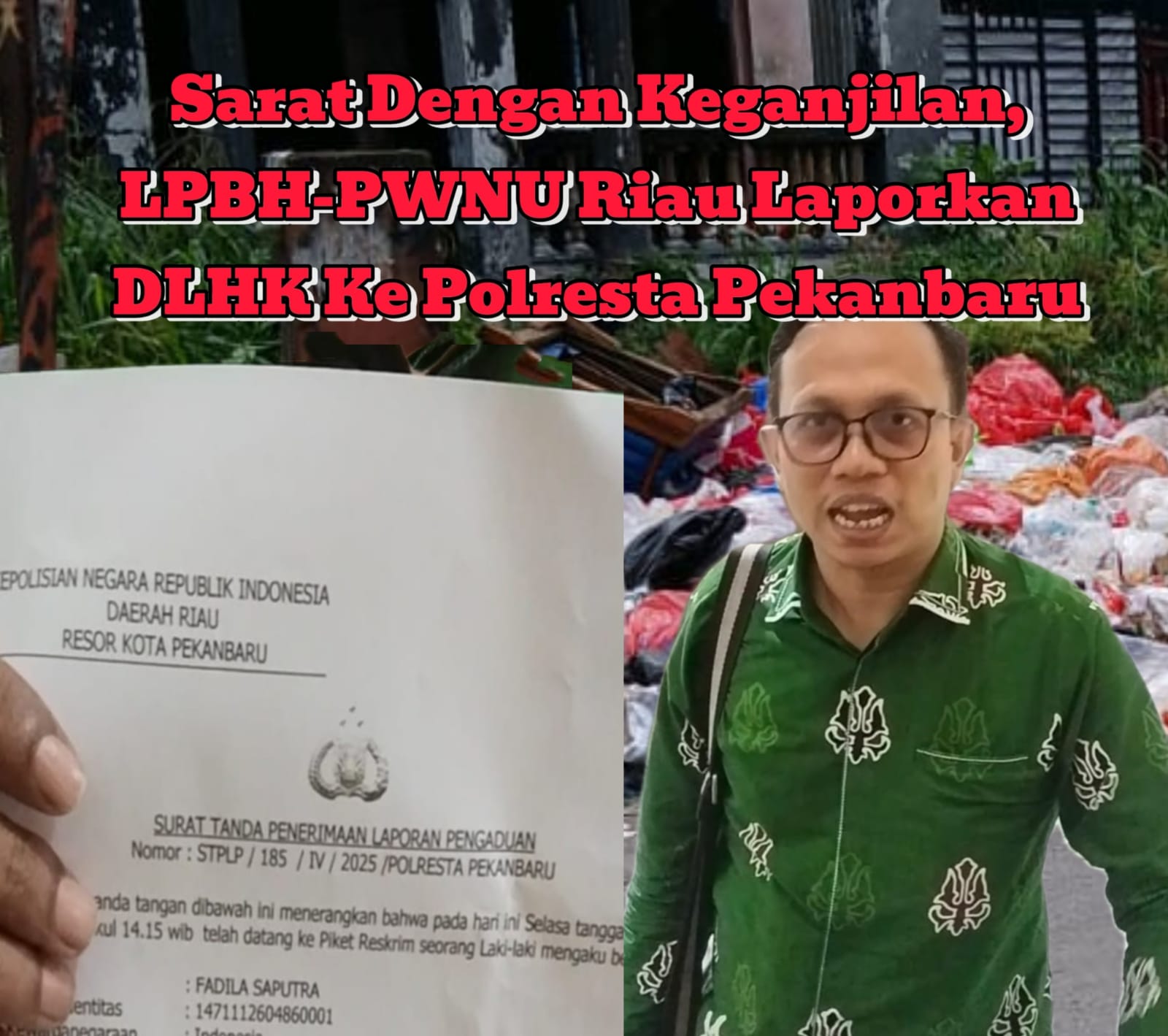











 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.


Tidak ada komentar