
 .
.

Iwakum Tantang Ketegasan UU Pers: Perlindungan Wartawan Masih Sebatas Retorika

Mataxpost | Jakarta – Di ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang biasanya sunyi dan tertib, perdebatan tentang masa depan kebebasan pers Indonesia kembali mencuat. Ketua Umum Ikatan Wartawan Kejaksaan dan Hukum Media (Iwakum), Irfan Kamil, menilai keterangan yang disampaikan DPR dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum menjawab substansi persoalan yang selama ini menghantui profesi wartawan: bagaimana negara menjamin perlindungan hukum yang nyata bagi mereka yang menjalankan fungsi kontrol sosial. (30/10)

Bagi Kamil, penjelasan yang diberikan Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, terlalu normatif sekadar mengulang semangat pembentukan UU Pers yang luhur, tanpa menyentuh sisi paling konkret dari implementasinya.
Dalam pandangannya, pernyataan semacam itu lebih mirip pengulangan retorika reformasi ketimbang jawaban atas realitas hukum yang dihadapi wartawan hari ini.
“DPR hanya menjelaskan maksud pembentukan UU Pers tanpa menjawab bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap wartawan dijalankan secara konkret,” ujar Kamil dalam keterangan tertulis yang disampaikan usai sidang.
Kamil menyoroti inti masalah yang menjadi dasar permohonan Iwakum, yaitu frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers. Bagi Iwakum, kalimat singkat yang berbunyi “wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya” menyimpan problem tafsir yang serius.
Frasa itu tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, tidak menjabarkan mekanismenya, dan tidak menggambarkan bentuk konkret perlindungan yang dimaksud apakah administratif, hukum, fisik, atau moral.
Dalam konteks hukum, kekaburan seperti itu bukan sekadar persoalan semantik, tetapi menyangkut kepastian hukum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, termasuk wartawan
“Kalimatnya kabur, Tidak jelas siapa yang memberi perlindungan, prosedurnya bagaimana, dan dalam bentuk apa”
Akibatnya, wartawan tetap berisiko dikriminalisasi dengan pasal-pasal pidana umum di KUHP,” tegasnya. Pernyataan itu tidak muncul dari ruang kosong. Sejak UU Pers disahkan pada 1999, berbagai kasus kriminalisasi wartawan terus terjadi.
Wartawan yang menulis kritik terhadap pejabat atau pengusaha kerap dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, padahal secara normatif semestinya mereka dilindungi oleh mekanisme etik Dewan Pers.
Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teks hukum dan realitas lapangan, antara janji perlindungan dan praktik penegakan hukum.
Pandangan Kamil sejalan dengan pengamatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, yang dalam sidang tersebut mempertanyakan alasan masih diperlukan nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum apabila norma perlindungan wartawan sudah tegas diatur dalam undang-undang.
Pertanyaan itu, menurut Kamil, mencerminkan kepekaan MK terhadap ketidaktegasan norma yang selama ini menjadi sumber ambiguitas.
“Ketua MK menganalisis mengapa perlindungan hukum wartawan masih harus diamankan dengan MoU kalau normanya sudah jelas. Itu menunjukkan memang ada masalah di tingkat norma,” katanya.
Koordinator Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menegaskan bahwa uji materi yang diajukan pihaknya bukanlah upaya melemahkan posisi wartawan atau mengutak-atik substansi UU Pers secara sembrono.
Sebaliknya, langkah ini dimaksudkan untuk mempertegas norma yang selama ini berada di wilayah abu-abu.
“Lucunya, justru organisasi-organisasi wartawan seperti Dewan Pers, AJI, dan PWI malah terlihat menolak upaya kami memperjelas norma yang melindungi wartawan. Padahal, tujuan kami murni memperkuat perlindungan hukum, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Viktor menilai penolakan itu menunjukkan adanya kekhawatiran berlebihan dari kelompok arus utama pers yang mungkin merasa posisi institusional mereka akan terganggu apabila tafsir norma diperjelas oleh MK.
Di sisi lain, organisasi wartawan seperti Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai bahwa persoalan utama bukanlah pada teks pasal, melainkan pada lemahnya implementasi perlindungan hukum di lapangan. Bagi mereka, UU Pers sudah cukup progresif.
Masalahnya, aparat penegak hukum sering kali tidak memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers, sehingga memilih jalur pidana alih-alih menggunakan mekanisme etik Dewan Pers. Dengan kata lain, menurut pandangan kelompok ini, undang-undangnya tidak salah yang salah adalah aparatnya.
Namun, bagi Iwakum, pandangan semacam itu justru menutup mata terhadap realitas bahwa kekaburan norma menjadi celah bagi aparat untuk menafsirkan seenaknya. Tanpa definisi yang tegas tentang bentuk perlindungan hukum, negara seperti memberi janji tanpa kewajiban.
Wartawan tetap berhadapan dengan risiko hukum yang tinggi ketika menjalankan fungsi kontrol publik, terutama dalam konteks politik dan ekonomi yang sensitif. Dalam situasi semacam itu, jaminan hukum yang kabur sama bahayanya dengan tidak ada jaminan sama sekali.
Perdebatan antara Iwakum dan organisasi wartawan mapan sejatinya menggambarkan pertarungan dua tafsir tentang bagaimana kebebasan pers seharusnya dijaga: apakah melalui penguatan norma hukum yang eksplisit, atau melalui peningkatan kesadaran aparat dan penerapan mekanisme etik secara konsisten.
Perdebatan ini sekaligus memperlihatkan betapa UU Pers 1999, meski menjadi tonggak reformasi, kini menghadapi ujian relevansi di era digital yang memperluas definisi “wartawan” dan “media”.
Dalam ruang media yang kini dihuni oleh jurnalis independen, pekerja lepas, hingga pembuat konten, perlindungan hukum yang kabur semakin terasa problematik.
Mereka yang bekerja di luar struktur redaksi besar sering kali tidak punya akses terhadap perlindungan institusional Dewan Pers, sementara aparat penegak hukum tetap menggunakan pendekatan pidana konvensional terhadap produk jurnalistik.
Uji materi yang diajukan Iwakum di Mahkamah Konstitusi dengan demikian bukan sekadar gugatan terhadap satu pasal, melainkan ujian terhadap cara negara memandang kebebasan pers: apakah sebagai hak yang harus dilindungi dengan instrumen hukum yang tegas, atau sekadar semangat moral yang dipercayakan pada tafsir pejabat dan aparat.
Jika MK kelak berani menafsir ulang frasa “perlindungan hukum” secara lebih konkret dan operasional, putusan ini bisa menjadi preseden penting bagi demokrasi Indonesia, menegaskan kembali bahwa kebebasan pers bukan kemurahan hati negara, melainkan hak konstitusional warga negara.
Tetapi jika MK menolak permohonan Iwakum tanpa catatan kritis, maka status quo akan tetap bertahan: wartawan akan terus berjalan di antara dua dunia kebebasan yang dijanjikan undang-undang dan ancaman hukum yang sewaktu-waktu bisa menjerat mereka.
Dua puluh enam tahun setelah disahkannya UU Pers 1999, perdebatan tentang perlindungan wartawan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berutang kepastian hukum kepada para penjaga ruang publik.
Di balik idealisme jurnalisme, ada kenyataan getir bahwa kebebasan berekspresi sering kali masih harus berhadapan dengan tafsir hukum yang lentur.
Dan selama perlindungan hukum bagi wartawan tetap kabur, kebebasan pers di Indonesia akan terus berdiri di atas fondasi yang rapuh dan rawan tumbang di pengadilan.






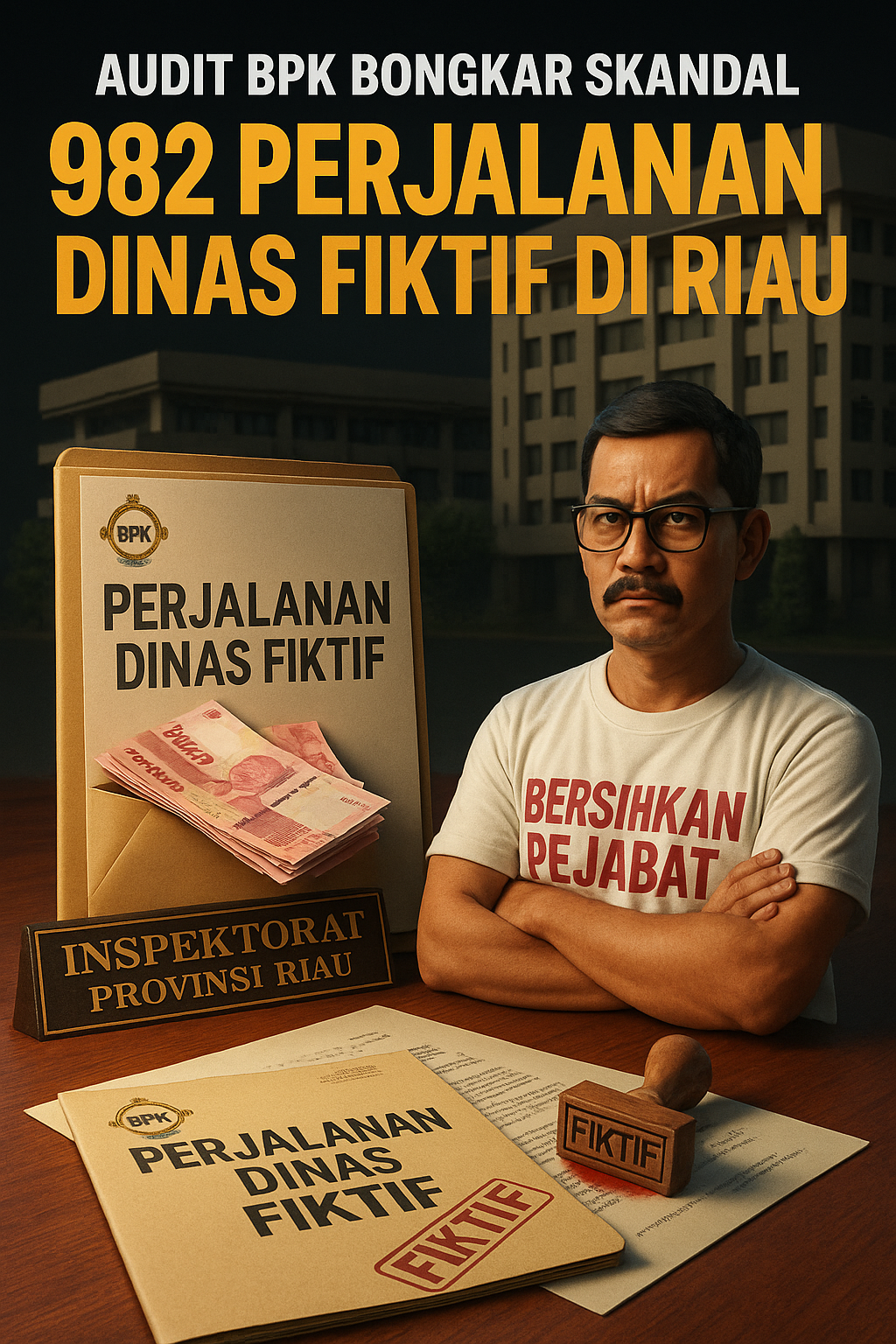




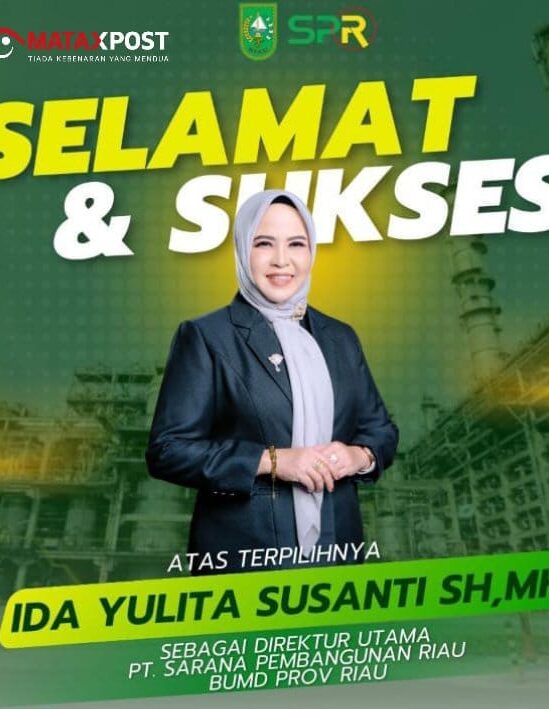


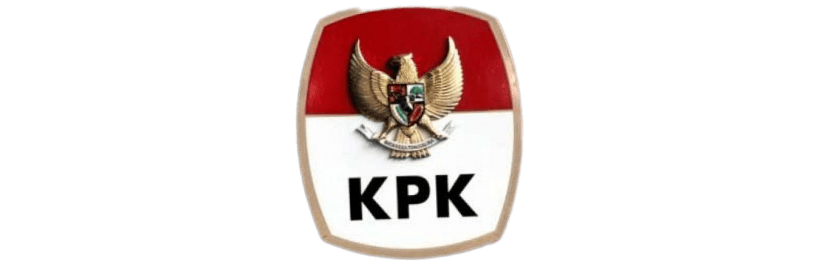










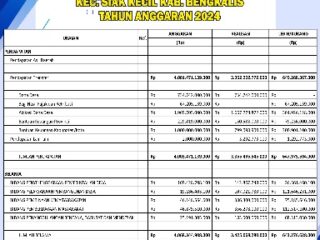
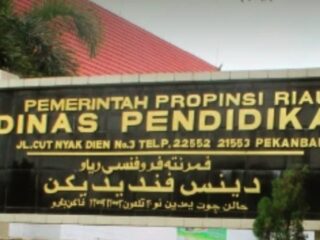


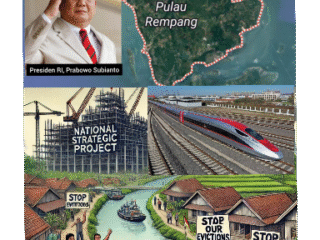




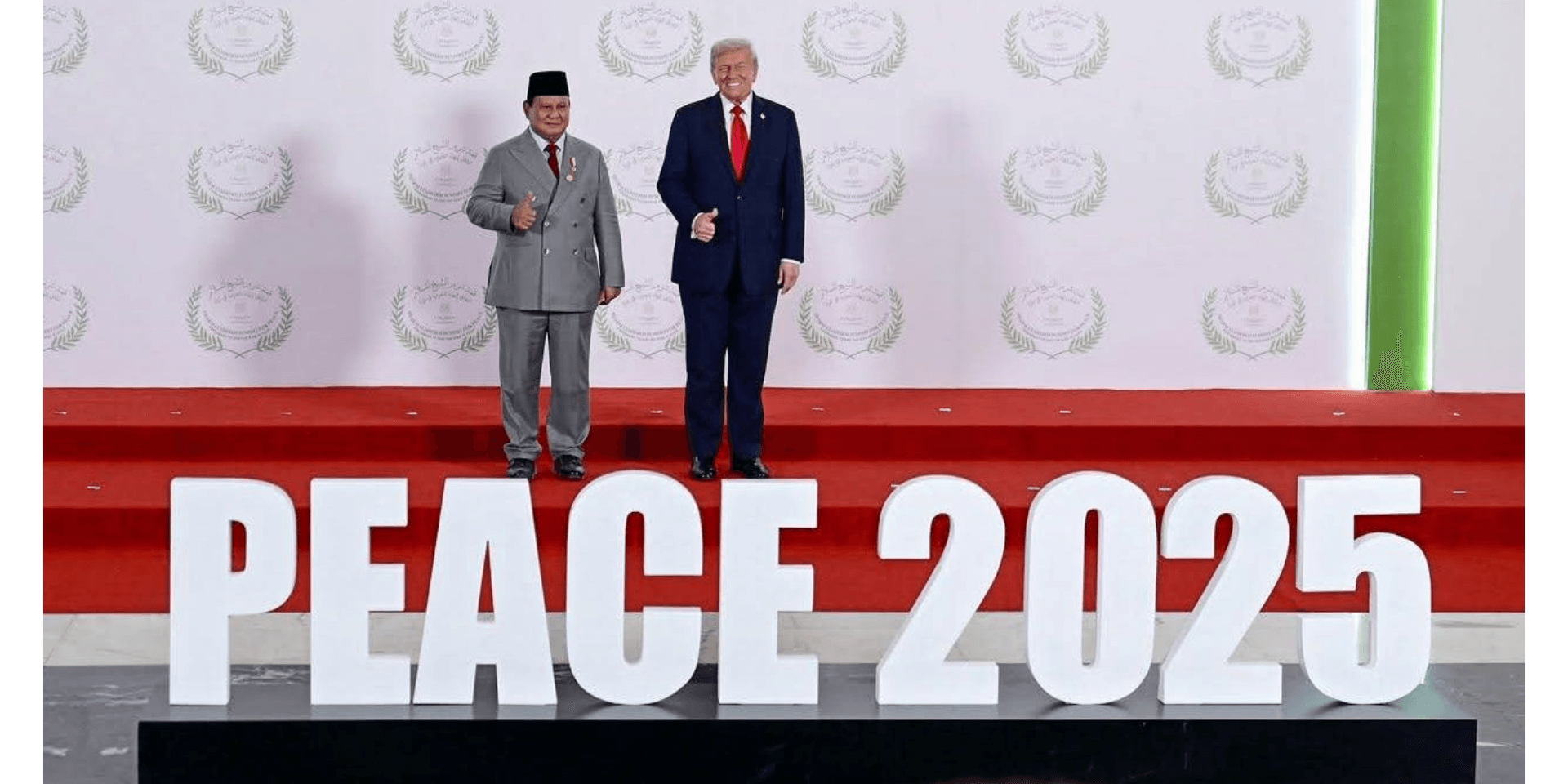
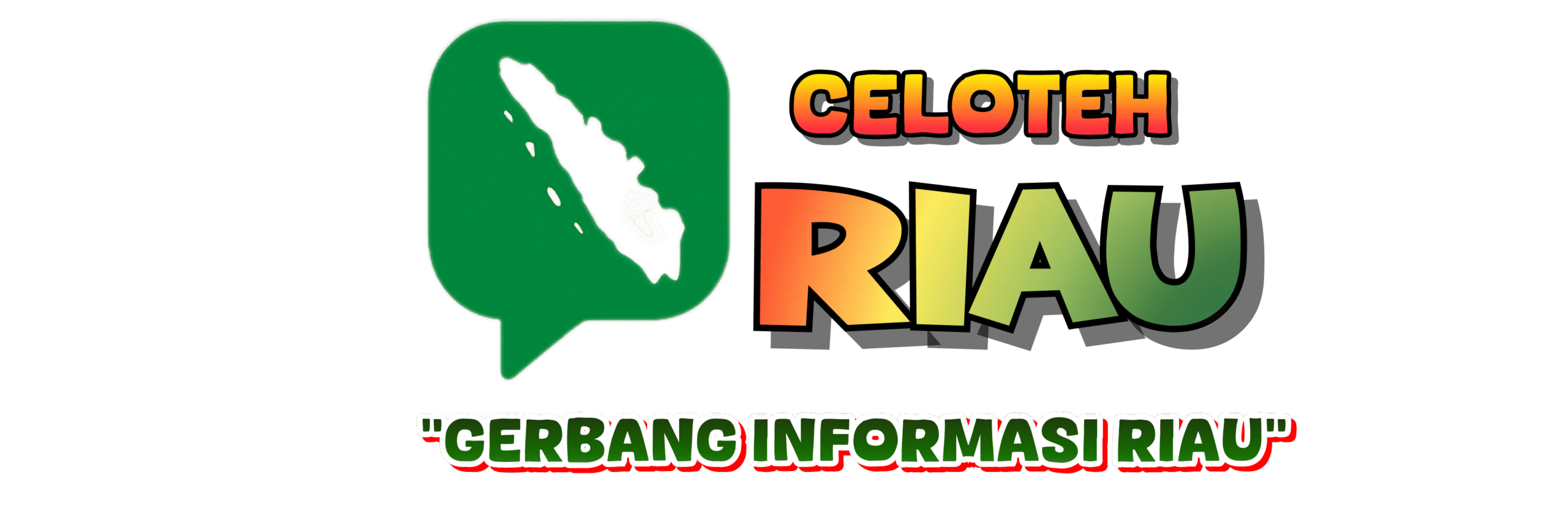


Tidak ada komentar