
 .
.
 .
.
 .
.

Reformasi Penegakan Hukum Mencuat, KPK Diminta Jujur di Tengah Tudingan Rekayasa

Mataxpost | Pekanbaru,- Pernyataan keras Noel yang menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan apa yang ia sebut sebagai “operasi tipu-tipu” kembali memantik perdebatan publik mengenai integritas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. Noel mengklaim dirinya menjadi korban rekayasa hukum, mulai dari pemanggilan yang disebut sebagai klarifikasi hingga penetapan status tersangka, penyitaan aset, serta pembentukan narasi publik yang menurutnya dibangun secara menyesatkan. (27/01)
Dalam pernyataannya yang dilansir dari Sindonews.com, Noel bahkan menyebut KPK lebih menyerupai “content creator” ketimbang lembaga penegak hukum, menurut Noel, konstruksi perkara terhadap dirinya sarat framing. Ia menyebut penyitaan kendaraan pribadinya kemudian dipublikasikan sebagai hasil pemerasan puluhan mobil.

Tidak lama berselang, muncul narasi lanjutan mengenai aliran dana ratusan miliar rupiah yang dikaitkan dengan namanya, meskipun, menurut pengakuannya, tudingan tersebut tidak pernah dibuktikan secara konkret di pengadilan.
Ia menyatakan siap menerima hukuman mati atau hukuman seringan-ringannya, seraya menegaskan bahwa korupsi pada dasarnya berakar dari kebohongan.
Tudingan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah perkara korupsi yang penanganannya tidak selalu berujung pada vonis bersalah. Salah satu kasus yang kini menjadi perhatian luas adalah perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Dalam operasi penangkapan terhadap Abdul Wahid, tidak ditemukan uang tunai sama sekali di lokasi. Fakta ini memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar penetapan tersangka serta kekuatan konstruksi pembuktian yang dibangun oleh penyidik.
Dalam praktik hukum pidana, ketiadaan uang tunai saat operasi tangkap tangan memang tidak serta-merta menggugurkan dugaan tindak pidana korupsi.
Penegak hukum dapat mendasarkan perkara pada alat bukti lain, seperti keterangan saksi, dokumen transaksi, hasil penyadapan, maupun penelusuran aliran dana tidak langsung. Namun, kondisi semacam ini menempatkan beban pembuktian yang jauh lebih berat pada jaksa penuntut.
Seluruh rangkaian peristiwa, kronologi, serta konsistensi narasi akan diuji secara ketat di persidangan. Ketidaksinkronan fakta, perubahan cerita, atau minimnya transparansi berpotensi melemahkan perkara secara signifikan.
Situasi inilah yang kemudian menjadi sorotan tajam publik dalam penanganan dugaan korupsi di Provinsi Riau. Laporan Mataxpost dari Pekanbaru menyebutkan bahwa hingga kini gejolak politik dan perkara hukum tersebut masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Publik Riau maupun nasional terus memantau perkembangan kasus dengan kecemasan tinggi, terutama karena narasi yang disampaikan KPK dinilai kerap berubah, sementara kronologi penangkapan dan penggeledahan dianggap membingungkan serta minim penjelasan terbuka.
Desakan agar KPK bersikap jujur, terbuka, dan konsisten semakin menguat. Tekanan tidak hanya datang dari media sosial, tetapi juga dari forum diskusi publik, kalangan mahasiswa, hingga pemerintahan lokal. Di tengah minimnya informasi yang jelas dan terverifikasi, berbagai asumsi dan spekulasi berkembang liar.
Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah dugaan adanya relasi tidak sehat antara KPK dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, yang kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.
Spekulasi ini memperuncing ketidakpastian hukum dan memunculkan pertanyaan serius apakah perkara tersebut murni penegakan hukum atau terseret dalam konflik politik lokal.
Kisruh di Riau berakar dari ketegangan politik berkepanjangan antara Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto. Ketegangan tersebut sempat dimediasi oleh Kapolda Riau.
Namun, hanya berselang beberapa hari setelah upaya perdamaian itu, pada 3 November 2025 Abdul Wahid ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang disebut tidak menemukan uang tunai sebagai barang bukti di lokasi.
Penangkapan mendadak ini memicu pertanyaan luas karena dinilai tergesa-gesa, tidak disertai penjelasan rinci mengenai dasar penindakan, serta menimbulkan kesan prosedural yang bersifat ad hoc.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Mataxpost dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, SF Hariyanto turut diperiksa pada hari penangkapan tersebut.
Keesokan harinya, pada 4 November 2025, Abdul Wahid, SF Hariyanto, dan Kepala Dinas PUPR Arif Setiawan dibawa ke Jakarta dengan penerbangan terpisah. Setibanya di ibu kota, SF Hariyanto dikabarkan dibawa ke sebuah rumah sakit Siloam, sementara Abdul Wahid langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.
Perbedaan perlakuan ini menambah kecurigaan publik akan adanya kejanggalan prosedural dan perlakuan hukum yang tidak setara.
Pada 5 November 2025, KPK menggelar konferensi pers dan menyampaikan bahwa Abdul Wahid diduga terlibat dalam praktik korupsi yang disebut dengan istilah “japrem” atau jatah preman.
Namun, paparan bukti yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut dinilai minim dan tidak memberikan gambaran utuh mengenai konstruksi perkara. Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Radiogram penunjukan SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau.
Keputusan ini semakin memperkuat spekulasi publik mengenai keterkaitan antara dinamika politik dan proses hukum yang sedang berjalan.
Perkembangan berikutnya justru memperlebar keraguan.
KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dinas dan rumah pribadi Plt Gubernur. Dalam penggeledahan tersebut, dilaporkan ditemukan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing, termasuk dolar, serta sejumlah dokumen.
Namun, hingga kini KPK belum menjelaskan secara terbuka jumlah pasti uang yang disita maupun relevansi dokumen-dokumen tersebut terhadap perkara utama. Ketertutupan ini memicu spekulasi baru, termasuk dugaan pengalihan isu dan manipulasi opini publik.
Kejanggalan lain muncul dari proses penahanan Abdul Wahid. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejak penangkapan, pemeriksaan substantif terhadap Abdul Wahid sangat terbatas, sementara masa tahanan terus diperpanjang.
Minimnya penjelasan mengenai perkembangan penyidikan menambah kesan bahwa perkara berjalan tanpa arah yang transparan dan terukur.
Polemik semakin memanas setelah beredarnya surat tulisan tangan yang diklaim berasal dari Abdul Wahid dari balik tahanan KPK. Surat tersebut berisi bantahan terhadap tuduhan serta kritik atas prosedur penanganan perkara. Surat ini beredar luas di media sosial dan grup percakapan.
Namun, sejumlah pengamat hukum menilai surat tersebut janggal dan berpotensi menyesatkan, mengingat ketatnya aturan komunikasi bagi tahanan dalam perkara KPK.
Rangkaian peristiwa ini menempatkan KPK dalam sorotan paling kritis dalam beberapa tahun terakhir. Sejarah peradilan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang ditangani aparat penegak hukum berakhir dengan vonis bersalah.
Pada 2022, Pengadilan Tipikor Pekanbaru membebaskan Suheri Tirta, Legal Manager PT Duta Palma Grup, dalam perkara dugaan suap perubahan tata ruang wilayah di Provinsi Riau.
Pada tahun yang sama, Pengadilan Tipikor Banda Aceh membebaskan empat terdakwa perkara pengadaan sapi senilai Rp3,4 miliar. Pengadilan Tipikor Medan juga memutus bebas Mujianto dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang senilai Rp39,5 miliar.
Pada 2019, mantan Dirut PLN Sofyan Basir diputus bebas di tingkat pertama dalam perkara PLTU Riau-1, sebelum diuji kembali di tingkat kasasi. Pada 2013, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad juga sempat diputus bebas dalam salah satu perkara yang menjeratnya.
Rangkaian putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa keyakinan penyidik dan tekanan opini publik tidak selalu sejalan dengan penilaian hakim di persidangan.
Hingga kini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan KPK terbukti secara sistematis melakukan rekayasa hukum.
Namun, fakta bahwa sejumlah perkara runtuh di pengadilan menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tetap harus terbuka terhadap koreksi.
Ironisnya, kekalahan KPK di pengadilan jarang dijadikan bahan evaluasi terbuka.
Tidak ada kewajiban hukum untuk mempublikasikan analisis kegagalan perkara, tidak ada audit independen atas dakwaan yang ambruk, dan tidak tersedia mekanisme akuntabilitas berbasis kualitas pembuktian. Yang kerap muncul hanyalah pernyataan normatif bahwa hakim memiliki pandangan berbeda.
Di sinilah kritik publik menemukan pijakan rasional. Kepercayaan publik tergerus bukan semata karena KPK kalah di pengadilan, melainkan karena kekalahan tersebut tidak pernah dipelajari secara terbuka.
Membubarkan KPK bukanlah jawaban, karena itu hanya solusi instan tanpa substansi. Reformasi tetap diperlukan, namun bukan dengan memotong kewenangan.
Reformasi yang relevan semestinya menyasar standar minimal pembuktian sebelum penetapan tersangka, kewajiban audit atas perkara yang divonis bebas, pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan untuk mencegah bias konfirmasi, serta mekanisme pertanggungjawaban profesional bagi penyidik dan jaksa tanpa mengkriminalkan kekalahan mereka.
Negara hukum yang dewasa tidak mengukur penegakan hukum dari seberapa sering lembaganya menang, melainkan dari seberapa jujur ia mengakui kegagalan dan memperbaiki metode kerja.
Di titik inilah kritik terhadap KPK seharusnya diarahkan: bukan pada narasi dendam atau sensasi, melainkan pada tuntutan akuntabilitas yang rasional, terukur, dan berpihak pada prinsip keadilan.
Pos terkait

Latest Post









 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.













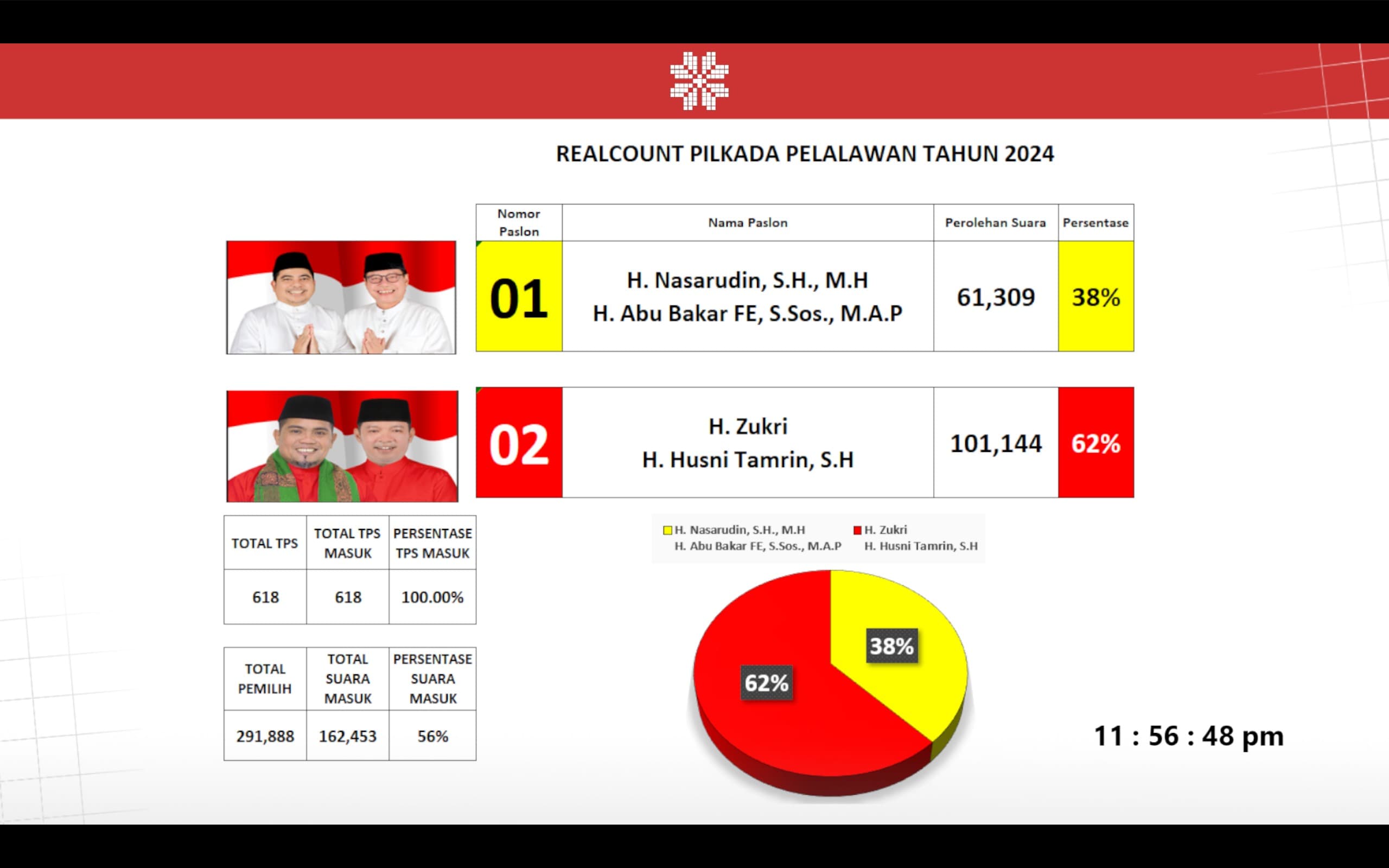


Tidak ada komentar